Belakangan banyak politisi dan pendukung timses tertentu yang amat mendewakan survei. Seakan-akan survei elektabilitas sudah pasti benar, patut dijadikan satu-satunya rujukan, dan sudah cukup menjelaskan siapa pemenangnya.
Beberapa yang lebih ngehe bilang “Udah coblos yang elektabilitasnya paling tinggi biar hemat biaya pemilu”. Atau “Milih koq yang udah pasti kalah, nanti suaramu sia-sia.”
Lah ngehe. Milih presiden koq disetir hasil survei. Goblok amat.
Apakah survei sudah pasti benar? Ya gak lah. Apakah survei memiliki muatan dan kepentingan tertentu? Bisa banget. Apa aja tuh? Nah mari kita bahas.
Di dunia yang ideal, survei harusnya bisa memberi manfaat ke kedua belah pihak: politisi dan publik. Publik bisa menyuarakan opini mereka, politisi bisa mendengar apakah kebijakan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat atau tidak. Tujuannya ya baik.
Sayangnya, kini politisi pun sudah cerdas. Mereka tahu betul cara untuk memanfaatkan survei. Baik untuk memanipulasi citra mereka atau menyetir opini publik. Bagaimana caranya? Pertama, dengan memunculkan kesan bahwa politisi tertentu amat disukai publik. Bahwa kandidat tertentu angka elektabilitasnya sangat tinggi. Presiden X angka kepuasan publiknya mencapai 99%. Kandidat B elektabilitasnya 55%. Begitu seterusnya. Bahwa mayoritas publik menyukai dan mendukung salah satu politisi, padahal kenyataannya tidak.
APPEAL TO MAJORITY
Kenapa mereka melakukan ini? Karena ada sesat pikir yang namanya appeal to majority. Bahwa sesuatu itu benar karena banyak orang menganggap demikian. “Lho mayoritas warga Bikini Bottom dukung Spongebob koq, masa sih mereka salah? Gue juga ikutan dukung ah.” Padahal, hanya karena sesuatu disukai oleh orang banyak, belum tentu itu benar. Appeal to majority sering digunakan karena itu efektif. Banyak iklan yang juga menggunakan trik serupa, koq.
“Jutaan orang telah menggunakan brand A”.
“Tujuh dari sepuluh perempuan memilih pembalut X”
“Sembilan dari sepuluh dokter gigi merekomendasikan kamu sikat gigi pakai cabe ijo”
Orang itu malas mikir. Maka mereka sebisa mungkin meng-outsource pilihan-pilihan mereka lewat jalan pintas. Salah satunya ya appeal to majority. Mereka menganggap bahwa banyak orang memilih sesuatu maka sesuatu itu pasti benar. Hal inilah yang dimanfaatkan politisi lewat survei-survei elektabilitas. Memunculkan kesan bahwa kandidat tertentu didukung mayoritas publik.
SURVEI ITU MAHAL
Menjalankan survei itu mahal. Banget. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia market research, saya tahu menjalankan riset dan mencari responden itu mahal. Melelahkan dan mahal. Jika ada lembaga survei yang reputasinya gak jelas, pendanaannya gak jelas, tapi rajin rilis hasil survei, patut banget dipertanyakan. Sponsornya siapa? Siapa yang mendanai? Kepentingannya apa? Para politisi juga tahu koq bahwa ada lembaga survei yang bisa dibayar.

Pertanyaannya, siapa yang punya dana melimpah untuk menyetir lembaga survei? Ya kita tahu sama tahu lah paslon mana yang balihonya paling masif. Iklan di media sosial, televisi, dan radio paling sering. Sanggup membayar deretan pesohor dan influencer besar. Bahkan di Harian Kompas hari ini sanggup menyewa dua halaman depan sekaligus. hehehe..
LEGITIMASI KECURANGAN
Survei juga bisa digunakan sebagai dasar bagi politisi untuk membandingkannya dengan hasil pemilu sesungguhnya nanti. Jika Pemilunya curang tapi hasilnya sesuai survei, mereka akan berkata “Tuh kan, sesuai sama survei, berarti pemilunya adil”. Sebaliknya, jika hasilnya berbeda mereka bisa menuding bahwa pemilu telah dicurangi karena tidak sesuai hasil survei. Trik ini pernah digunakan oleh Donald Trump.
SURVEI YANG SALAH
Kita bisa belajar dari sejumlah kasus dimana survei bisa salah besar. Jauh berbeda dari hasil di lapangan. Literary Digest di tahun 1936 dengan salah memprediksi hasil Pemilu Presiden AS. Respondennya sangat besar, lebih dari dua juta orang! Survei memprediksi Landon akan mengungguli Roosevelt, 57%-43%. Roosevelt akan kalah jauh. Ternyata, hasil Pemilu sesungguhnya malah Roosevelt unggul telak di angka 62%!
Survei di Inggris kala Pemilu 2015 juga salah. Begitu pun survei-survei di Amerika Serikat beberapa Pemilu terakhir yang hasilnya berbeda dengan kenyataan. Bahkan sampai dibahas di kalangan akademisi. Yang mempertanyakan isu fundamental riset dan metodologi problematik yang seringkali luput dari perhatian para lembaga survei.
RANDOM SAMPLING
Kenapa survei bisa salah? Analisa terhadap sejumlah kasus kesalahan lembaga survei bisa menjadi acuan. Survei bisa merepresentasikan masyarakat dengan baik jika mereka mampu melakukan random sampling. Yakni pemilihan sampel secara acak. Artinya setiap anggota di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden.
Jika kamu menyurvei siapa guru favorit di sebuah sekolah, maka kamu harus memastikan semua murid di sekolah tersebut bisa menjadi responden. Kalau kamu mengambil datanya hanya di lapangan basket, ya tidak random sampling. Hanya murid-murid yang ke lapangan basket yang berkesempatan menjadi responden. Kalau kamu mengambil datanya di kantin, ya hanya mereka yang suka jajan yang berkesempatan jadi responden. Asas utama random sampling-nya sudah tidak terpenuhi.
Kesalahan ini yang dilakukan oleh Literary Digest puluhan tahun lalu, yang masih suka diulang oleh lembaga survei hingga kini. Meski mereka mengambil sampel sangat besar, yakni 2 juta responden, nyatanya asas utama random sampling tidak terpenuhi. Kenapa? Karena mereka memilih sampelnya lewat database pemilik mobil pribadi & telepon rumah.
Pada masa itu, keduanya HANYA dimiliki oleh kelompok menengah ke atas saja. Di tahun 1936, mobil pribadi dan telepon rumah masih jadi barang mewah. Tidak semua orang memilikinya. Sehingga mereka-mereka yang jadi responden pun sudah terseleksi dengan sendirinya. Masyarakat pada umumnya tidak berkesempatan jadi responden. Sehingga suara mereka tidak terrepresentasikan dengan baik.
Kebanyakan survei saat ini mengambil data lewat dua hal: tatap muka langsung & sambungan telepon. Tahu apa yang bermasalah dari cara ini? Hanya orang-orang dengan karakteristik tertentu yang akhirnya berpotensi jadi responden. Tidak semua orang ketika ditanya di pinggir jalan mau membagikan pilihan politik mereka. Tidak semua orang mau mengangkat telepon dari orang tidak dikenal, lebih-lebih menyampaikan pilihan capresnya.
Saya yakin kebanyakan orang akan menolak saat disurvei. Ada yang merasa itu privasi. Ada yang merasa tidak nyaman membagikannya ke orang lain. Ada yang takut jawabannya akan mempengaruhi bansos & bantuan negara baginya. Hal ini terjadi koq di lapangan, salah satu lembaga survei batal merilis survei elektabilitas karena banyak yang menolak menjawab.

Sayangnya, tidak semua lembaga survei melakukan hal ini. Jika ada yang menolak, mereka akan lanjut ke responden berikutnya. Jika ada yang tidak bisa dihubungi, mereka akan mengontak responden berikutnya. Pada akhirnya, terjadi sampling bias karena yang menjawab ya mereka-mereka yang punya karakteristik tertentu saja. Misalnya yang all-in sama pilihannya dan tidak akan mendapatkan intimidasi apa-apa karena jawabannya. hehe
Gak percaya sama saya ya gak apa, kamu bisa baca-baca buku atau jurnal ini:
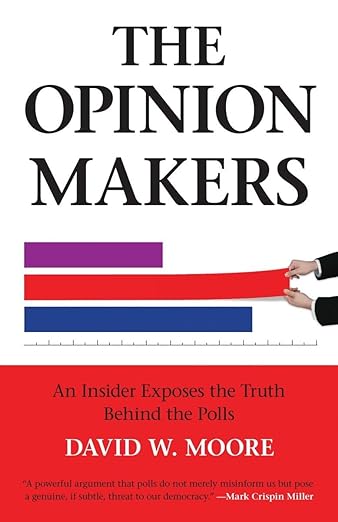

Intinya, jangan mau dibego-begoin sama survei. Jangan percaya gitu aja sama hasil survei. Apalagi dibego-begoin bahwa percuma kamu memilih kandidat tertentu karena suaramu akan sia-sia. Atau disuruh dukung salah satu kandidat aja biar menang satu putaran dan hemat biaya pemilu.
Gak ada suara yang sia-sia, dan harga demokrasi lebih tinggi dari sekadar berhemat belasan triliun.
Lagian, belum tentu koq Prabowo-Gibran elektabilitasnya di 52%.
Siapa tahu ternyata sebenarnya tuh udah tembus 170%.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tulisan berikutnya!
Jakarta, 9 Februari 2024
Kirim Komentar!